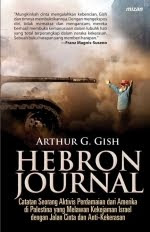
Judul : Hebron Journal;
Catatan Seorang Aktivis Perdamaian dari Amerika yang Melawan Kekejaman Israel di Palestina dengan Jalan Cinta dan Anti-Kekerasan
Penulis : Arthur G. Gish
Penerbit : Mizan, Bandung
Cetakan : 1, Juli 2008
Tebal : 550 halaman
Israel membombardir kawasan Gaza menyisakan luka mendalam, berdalih menimpali kiriman roket Hamas menjelang pergantian tahun kemarin. Banyak properti terutama rumah penduduk yang kemudian luluh-lantak. Parahnya, serangan ngawur itu turut menyasar nyawa seribu lebih warga sipil; mayoritas perempuan dan anak-anak. Ribuan korban sisanya terluka serius hingga terancam kehilangan masa depan. Kecaman luas masyarakat internasional plus sempritan keras PBB pun urung sanggup menyetopnya. Justru gudang penyimpanan bantuan dan sekolah PBB ikut menjadi bulan-bulanan.
Para sedulur jengkel, nelangsa, atau gregetan menyikapinya? Wajar, itu tandanya Sampean masih waras, asal jangan terlalu senewen sambil mencak-mencak di jalanan. Mengingat, untuk kesekian kalinya merebak tragedi kemanusiaan yang sejatinya wajib senantiasa dicegah oleh penghuni jagat berlatar belakang takdir sosial apapun. Lebih-lebih percik konfrontasi sesekali masih menyalak usai genjatan senjata resmi dikumandangkan (sepihak) oleh Israel pada 18 Januari 2009 lalu. Edan!
Entah mengapa kabut permusuhan seolah enggan sirna dari langit Palestina? Apa yang mengendapkan bara pertikaian di bumi yang mengabadikan rekam jejak para Nabi umat Islam, Kristen, serta Yahudi itu sebenarnya? Di mana nurani rezim Zionis saat nafsu purba merabunkan nalar sehat mereka? Sampai kapan petaka demikian terus dibiarkan bakal terulang sewaktu-waktu kelak? Benarkah serpihan cinta telah musnah untuk selamanya di sana? Akankah tersisa sejumput harapan merentang kebersamaan hidup esok yang lebih mendamaikan?
Nah, ketimbang suntuk berteka-teki melulu, alangkah baiknya sejenak membaca buku ini. Ya, sebuah jurnal apik torehan seorang aktivis perdamaian asal USA, Arthur G. Gish, ketika pernah lima kali bergumul dalam geliat konflik Israel-Palestina di Kota Hebron tahun 1995-2001 silam. Mendaras santai laporan pandangan mata yang cukup rinci, komplit dengan sederet foto yang menyentuh perasaan ini, pikiran akan terangsang meresapi sengkarut hubungan dua bangsa bertetangga dekat tersebut lewat perspektif yang agak berbeda, seru, dan maknyus. Siapa tahu nanti juga menemu relevansinya untuk ngudar benang kusut krisis Gaza mutakhir. Asyik!
Lebih mengasyikkan lagi, Art –begitu penulis risalah ini akrab disapa– berbagi pengalamannya menunaikan “plesir suci” menempuh jalan cinta, demi mengembuskan kembali ruh Kota “Sahabat”, bersama sesama anggota Christian Peacemaker Teams (CPT). Serupa lelaku kaum sufi yang meniti hub (cinta) sebagai anak tangga puncak guna membentangkan kedamaian bagi segenap insan. Dan ia memulainya dengan sering mengajak masyarakat setempat berdialog; kendati berulangkali harus menanggung cemoohan, semburan benci, bahkan ancaman gorok dari settlers Yahudi.
Ups, dari catatan harian ini pula kita dapat belajar sejumlah rahasia kecil. Mau? Antara lain, tentang potret sosial pemukim Hebron yang bisa jadi terpindai pada generasi Israel kontemporer. Mungkin dari sono-nya umumnya mereka cenderung suka usil, mbethik, narsis, semau gue, provokatif, raja ngeyel, serta gemar mengoarkan kabar bohong. Selain itu, mereka mengalami kekosongan rohani (hal. 160) ditambah gejala hilangnya selera humor. Usut punya usut mereka diwarisi beban psikologis amat traumatik bawaan kegetiran historis jadul, sehingga dipenuhi kebencian untuk kemudian selalu parno berkarib orang-orang Palestina. Mereka pun lantas demen menindas, mencaplok pekarangan, bahkan meneror warga Palestina demi rasa aman yang anehnya berkedok doktrin agama yang elusif dan antagonistis.
Di pihak lain, komunitas Palestina dibayangi riwayat kuno yang hampir sama. Tapi, mereka –tanpa bermaksud membesar-besarkan– lebih bisa nrima atau memilih bersikap defensif. Hanya saja, beragam teror imigran Yahudi, kadang akhirnya menjebol emosi mereka untuk meladeni. Dari sini, rawan terjadi gontok-gontokan antara kedua pihak. Gawat!
Apa yang mesti dilakukan? Di tengah ketegangan yang acap sulit dikendalikan macam itu, biasanya Art beserta timnya merasa perlu memainkan jurus-jurus kreatif mencegah anarkisme. Contoh, melontarkan banyolan segar, bermain sepakbola mini bareng anak-anak Palestina dan serdadu Israel, kucing-kucingan menghindari tentara Zionis, melempar-lempar bola gabus, meniup gelembung sabun, dan lain-lain untuk melumerkan suasana hati (hal. 122, 152, 157, dll). Hasilnya lumayan tokcer.
Bukan hanya itu, Brother Art juga kerap berani tampil menggugat obrakan rumah, rasisme, apartheid, pendudukan, ethnic cleansing, maupun bantustans terhadap keturunan Palestina yang ironisnya sering diabaikan oleh aparat Israel (hal. 173, 182, 221, dll). Ia menolak segala praktik dehumanisasi melalui upaya non-kekerasan berbekal ghirah cinta; walau harus masuk bui, ditodong bedil atau moncong tank. Ia pun getol menanamkan pengertian kepada banyak orang supaya menjauhi aksi balas-membalas karena tak akan menyudahi kekerasan. Sebagaimana kelakar Martin Luther King bahwa mata untuk mata dan gigi untuk gigi, hanya bakal membikin semua orang buta dan ompong (hal. 146).
Toh, realitanya secara personal butiran cinta masih berkelip di sela-sela kondisi yang mencekam. Coba tengok saat prajurit Israel menolong cedera bocah Palestina setelah jatuh dari sepedanya, warga Palestina menutupkan pintu kandang milik pemukim Yahudi agar hewan-hewan peliaraannya tak kabur, warga Israel yang datang minta maaf atas tindakan pemerintahnya kepada satu keluarga korban penghancuran rumah sembari menawarkan bantuan untuk membangunnya ulang, dan seterusnya (hal. 87, 285, dll). Sama halnya ketika unjukrasa damai berupa puasa massal atau “Tanah dalam Ember” guna menentang penggusuran rumah warga Palestina menyatukan kalangan berlainan etnis, negara, dan agama. Tak kecuali anggota Hamas dan Fatah.
Rahasia kecil lainnya tersirat pada indikasi kebohongan –seperti gerakan Hak-Hak Sipil di Amerika– yang melingkupi Hebron, atau tetap berlaku jamak sekarang? Di antaranya, pemikiran bahwa kaum Palestina adalah teroris, tanah Hebron (juga dataran se-Palestina?) diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Yahudi, bangsa Yahudi-Palestina tak bisa hidup bersama dalam damai, serta keamanan berasal dari senjata (hal. 200).
Yang mesti digarisbawahi, konflik di Hebron –bukan mustahil juga agresi di Gaza kali ini– sesungguhnya bukanlah tentang masalah agama. Namun, terkait ketidakadilan (hal. 414) yang lantas kerap dijadikan komoditas politik oleh rezim dan faksi penguasa oportunis untuk mengukuhkan kekuasaan. Kemudian pendekatan resolusinya monoton, represif, militeristik, serta melibatkan kepentingan asing seperti Amerika. Belum lagi, penggunaan senjata hingga jenis terlarang (hal. 474) yang justru sekadar melanggengkan kekerasan. Sementara, proses perdamaian (level elit) tak jarang semata tipuan. Busyet!
Jangan khawatir, masih banyak harapan membenahi keadaan tersebut. Mulanya butuh tekad kolektif menyingkirkan bayangan kelam sejarah masa lalu. Selanjutnya, mengembalikan kedaulatan kepada rakyat masing-masing guna mengikhtiarkan perdamaian secara dialogis, saling menghargai, dan anti-kekerasan. Tapi, kudu disadari penetrasinya menuntut serangkaian akselerasi kreatif yang bukan sebatas seni, melainkan sebentuk doa (hal. 215). Laiknya kesalehan pribadi, spiritualitas lintas batas, berpadu tapa brata seorang Art dalam membumikan cinta. Jadi, tampaknya orang-orang Israel dapat bertahan dengan orang-orang Palestina, senada ungkapan Jimmy Charter (sempat mengunjungi Hebron tahun 1995) bahwa Israel bakal hancur tanpa Palestina (Jawa Pos, 28 Januari 2009).
Coba saja pemerintah kita sanggup menghadirkan Ehud Barak, Tzipi Livni, Khaled Mashal, Hillary Clinton, Mahmud Abas, dan beberapa tokoh penting Yahudi-Palestina lainnya; dalam acara “Perayaan Cinta” selama tujuh hari tujuh malam yang dimeriahkan pula dengan seabrek lomba heboh, semisal panjat pinang atau tarik-tambang di lapangan berlumpur yang diwasiti Om Jojon di tanah air, yakin harapan atas semakin benderangnya kerlip cinta di Palestina akan kian terbuka lebar. Lagi pula, hari gini masih perang? Plis deh! Selebihnya, rugi besar jika belum menyimak sendiri diary tragikomedi yang sip-markosip ini, euy!






0 comments